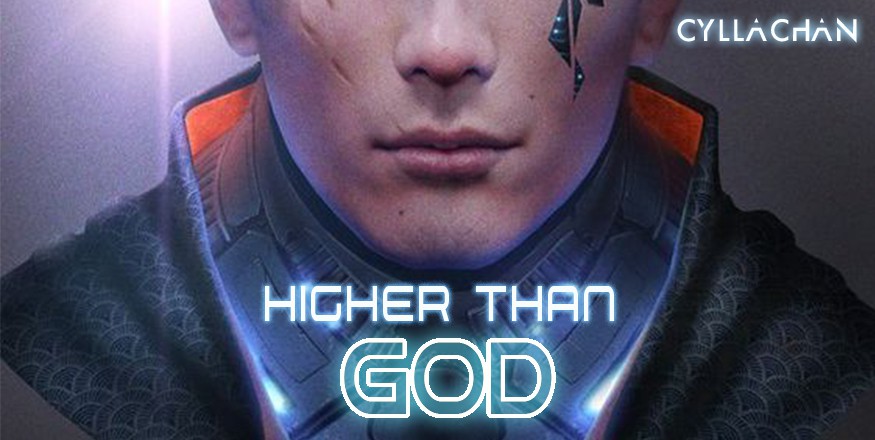"Ibu ... kenapa ayah tidak ada?" pertanyaan itu lagi. Kali ini terlontar di meja makan dengan pencahayaan yang redup. Di dalam sebuah unit apartemen kecil di pinggiran Distrik Beirut. Gadis muda itu belum menyentuh sup hangat di depannya.
Wanita yang tengah menyendoki sup dari panci ke mangkuk kecilnya terhenti sejenak. Ia merenung sekilas, lalu perlahan berusaha mengembangkan seutas senyum di bibirnya. Gadis itu masih menatapnya dengan kosong. Wajahnya datar. Ia menanyakan itu, namun seolah tak mengharapkan jawabannya. Hanya ingin bertanya saja.
"Kenapa Lin? Apa kau tidak betah tinggal berdua sama ibu?" tanyanya masih dengan sebuah senyuman. "Ini kan liburan musim panasmu dari akademi. Ibu sudah masak sup lentil untukmu, tapi kau malah jadi murung begini."
Ia menggeleng. "Teman-temanku di akademi punya ayah, tapi aku tidak," singkatnya. Matanya tak lagi menatapi wanita itu. Tangannya mulai menyendokkan sup lentil berwarna kekuningan ke dalam mulutnya. "Aku cuma ingin tahu saja ayahku seperti apa."
Perempuan di depannya menarik nafas panjang, namun masih berusaha mempertahankan senyumannya. "Ibu kan sudah pernah bilang, ayahmu itu pergi ke Koloni Mars saat ibu mengandungmu. Sudah, sudah ... makan saja dulu yang banyak. Habis ini kau bisa nonton film kung fu sepuasnya!" Setelah itu hanya dentangan kecil alat makan saja yang terdengar.
Bohong. Kau pembohong!
Kini ia sudah duduk di sofa tua dengan memandangi film kung fu yang dibintangi oleh artis terkenal, Chou Chou. Sebuah cakram holovid (hologram video) tergeletak di meja kecil di depan sofa dan menayangkan adegan pembuka film itu. Gambar hologramnya terkadang tidak stabil dan berdistorsi karena cakram itu sudah tua. Ia sudah sering menontonnya, mungkin lebih dari lima kali mengulang-ngulang film kung fu Chou Chou. Tampilan holovid yang tak stabil itu membuatnya enggan untuk menonton lagi.
Gadis itu beranjak. Ia menghampiri pintu kamar ibunya yang terbuka. Wanita itu sedang berdandan memandangi satu-satunya cermin di ruangan itu, tepat di depan meja riasnya. Tak berkata apapun, ia hanya bersandar pada bingkai pintu dan memperhatikannya. Setelah selesai memoles bibirnya dengan lipstik, ia baru sadar.
"Apa yang kau lakukan di situ?" tanyanya sambil memandangi putrinya dari pantulan cermin.
"Mau kemana?"
"Oh ... ibu ada shift malam di toko ayam. Kan bukanya dua puluh empat jam," jawabnya agak lantang agar terlihat wajar dan santai.
"Harus pakai baju begitu?" tatapannya mendikte rok span ketat di atas lutut, yang saat duduk pun memperlihatkan sebagian pahanya.
"Ibu kan kasir, paling depan. Jadi harus cantik! Kalau malam biasanya mulai ramai," ucapnya dengan nada yang ceria. Ditambah lagi senyuman cerah dengan wajahnya yang sudah cantik. "Sini-sini ... kemari," tangannya melambai-lambai cepat sekali meminta putrinya mendekat.
Gadis itu melangkah malas masuk ke dalam kamar. Tubuhnya sudah ditarik ke depan cermin meja rias itu. Melihat wajahnya sendiri yang lusuh, kosong, dan sama sekali tak bersemangat. Rambutnya pun berantakan. Bagai bumi dan langit jika dibandingkan dengan wanita di sebelahnya.
"Lin, coba perhatikan. Kau itu cantik sekali. Lebih cantik dari ibu. Sini coba ibu pakaikan lipstik," dengan cekatan ia meraih rahang gadis itu sekaligus memoles-moles ujung lipstik pada permukaan bibirnya.
Lin sudah pasrah, setengah dari wajahnya masih bisa melihat bayangan di cermin itu. Ia bisa melihat seluruh perlakuan ibunya pada kedua bibirnya. Kini bibirnya terlihat merah, penuh, dan lebih dominan.
"Lihat kan?! Cuma pakai lipstik saja sudah cantik. Kalau kau bisa berdandan apa lagi!" Lengan wanita itu sudah memeluk putrinya yang baru saja ia dandani sedikit dengan bangga.
Keduanya menatap bayangan mereka dari cermin itu. Ketika begini, mereka berdua nyaris terlihat sama.
"Lihatlah ... kau sudah besar. Sudah tujuh belas tahun. Dengan wajah ini, kau bisa mendapatkan pria manapun yang kau mau. Lalu kau bisa hidup enak, punya uang banyak, bisa beli apapun. Semua laki-laki akan melakukan apapun untukmu," senyum ibunya menjadi tajam dan berapi ketika mengucapkan kalimat barusan.
Lin membalas tatapan kosong mata hitamnya dari cermin itu.
Hidup enak? Uang banyak?
Jam menunjukkan pukul 20.18. Ia sudah enek melihat Chou Chou melakukan adegan yang sama itu lagi itu lagi. Meski ia sangat menyukai film itu, namun baginya ia sudah muak. Ditambah dengan cakram holovid-nya yang sudah butut. Ia tambah malas. Kini kakinya melangkah menyusuri gang-gang kecil yang sepi di pinggiran Distrik Beirut. Gadis itu melewati gang yang familiar baginya. Jalan menuju toko ayam dimana ibunya bekerja.
Tak berapa lama ia tiba di sebuah jalanan yang agak besar, yang agak ramai. Kedua tangannya masih tersimpan di dalam saku. Kakinya sesekali terseret malas ketika berjalan. Beberapa orang terlihat nongkrong-nongkrong di depan pertokoan. Sambil memakan camilan, menyeruput secangkir kopi, dan berbincang-bincang. Matanya mencari-cari dan berusaha mengingat letak toko ayam itu. Ketemu.
Tutup.
Gadis itu berdiri mematung di depan sepetak bangunan kosong yang sudah ditutupi gerbang rana aluminium dengan rapat. Kepalanya masih mendongak dengan lipstik yang belum ia hapus. Ia tak tahu harus bagaimana atau berbuat apa saat itu.
"Mau beli ayam? Yang punya sudah meninggal sebulan yang lalu. Sudah tidak jualan lagi," sahut seorang pria dari seberang jalan yang tengah memberikan sebotol bir pada pelanggannya di depan kios. Gadis itu menoleh singkat, lalu kembali menatapi toko ayam yang tutup itu.
Pembohong.
Jam dua pagi, namun ia hanya bisa menatapi langit-langit kamarnya yang sempit dekat tempat cuci baju. Tidak bisa tidur, tidak merasa mengantuk juga. Lampu kamarnya masih menyala.
Tiba-tiba ia mendengar suara gaduh dari ruang tengah. Terdengar beberapa barang berjatuhan menimpa lantai. Suara ketukan hak sepatu juga tak kalah di malam yang sunyi itu. Gadis itu menjadi waspada. Meskipun ia sudah tahu siapa yang datang.
Ia beranjak dari kasurnya yang kusam, lalu menuju ke ruang tengah. Dari sana ia bisa melihat pintu kamar ibunya terbuka. Gadis itu kini sudah berdiri di samping bingkai pintu.
Ibunya terduduk di depan meja riasnya. Dari cermin ia bisa melihat wajah wanita itu tertunduk. Tangannya memegangi kain sambil menekan pelipis kanan. Berdarah, tepat di sebelah matanya. Wanita itu mengangkat wajahnya. Riasannya sudah rusak. Eyeliner-nya luntur, mungkin karena keringat atau bekas air matanya. Warna hitam terlihat meleleh tepat di kantung matanya. Wajahnya merah dan matanya sendu.
"L-Lin ... apa ibu membangunkanmu? Maaf ya ... kembalilah tidur," ucapnya sambil melempar senyum yang sangat berat. "Ibu tak apa-apa," imbuhnya. Seandainya gadis itu menanyakan keadaannya.
"Tadi aku pergi ke toko ayam." Gadis itu menatapinya tanpa memasang ekspresi apapun. Hambar. "Tokonya tutup," lanjutnya.
Wanita itu tak lagi menatap gadis itu dari bayangan cermin. Ia memilih menghiraukannya, seolah pertanyaan itu tak pernah ada. Seperti segala pertanyaan tentang ayahnya. Senyumannya sudah tidak ada lagi. Kini ia sibuk membersihkan darah dari pelipisnya.
"Ibu habis melacur?" tanyanya pelan, ekspresinya datar.
Ia mendengkus sembari menyeringai mendengar hal itu. "Kau dengar dari siapa, Lin? Omongan orang jangan kau percaya ...," tangannya kini sedang menghapus eyeliner-nya yang meleleh dengan kertas tisu. Darah di lukanya sudah agak membeku.
"Aku sudah tahu kalau ibu pelacur." Kata-katanya begitu cepat hingga tak bisa dengan mudah untuk disanggah. Tangan yang dari tadi sibuk menyapukan kertas tisu di wajah, kini terhenti. "Sampai berapa orang yang sudah bercinta dengan ibu? Sampai ibu tak tahu ayahku yang mana?"
Wanita itu secepat kilat bangkit dari kursinya, membalik badannya dan melangkah cepat-cepat ke arah si gadis muda.
Tangan wanita itu terangkat tinggi-tinggi, berayun dan beradu dengan pipi putihnya. Secepat itu, sesingkat itu, dan sekencang itu. Ia terkejut, disusul dengan rasa nyeri dan panas di kulitnya yang memerah. Namun sensasi fisik itu masih tak sebanding dengan pilu yang menusuk-nusuk sukmanya.
Bunyi tamparan itu melengking di antara keheningan malam. Hingga suaranya memenuhi seisi ruangan kecil itu. Wajah putih Lin sudah menoleh ke kanan, meninggalkan sebuah bekas tamparan mantap pada pipi kirinya.
Air muka perempuan itu sudah bengis. Bau alkohol menyeruak dari tubuhnya saat mereka berdekatan.
"Anak kurang ajar!" pekiknya. "Kau pikir jika aku tidak melacur kau akan bisa tidur di kamarmu?!" tangan wanita itu ganas meraih rahang Lin, mendekatkan wajah mereka berdua.
Mata wanita itu menantangnya, menghujamkan seluruh pandangannya lekat-lekat. "Kau pikir aku bisa beli apartemen kalau kerjaku cuma di toko ayam busuk itu, hah?!"
Cengkraman itu mendorong wajah putih Lin kencang, membuatnya hampir terjerembab ke belakang. Kakinya reflek menahan tubuhnya agar tak terjatuh.
Wanita itu tertawa, terkekeh, lalu terbahak-bahak seperti orang gila. "Hahaha! Sudah jadi orang pintar kau sekarang ya. Kau diajari apa saja di akademi orang aneh itu? Diajari mencibirku?!" wanita itu menatapnya jijik.
Tubuh Lin memaku, ia tak berkata apa-apa. Wajah putihnya ketakutan, tangannya gemetar. "Kalau kau bukan anak terkutuk sialan dan harus ke akademi, memangnya kau bisa apa?" tawanya sudah lenyap, namun seringai gilanya masih ada.
Tangannya kini mengelus pipi putih gadis itu, menyusuri inci demi inci kulit putrinya yang mulus.
"Tentu saja, kau bisa kujual. Seharusnya sekarang aku bisa menontonmu dipakai beramai-ramai oleh laki-laki di distrik ini. Aku tak harus melacur lagi, karena menjualmu saja sudah cukup." Nada bicaranya melembut, tetapi terdengar menjijikan. Sangat menjijikan.
Nafas gadis itu tak beraturan, ia shock. Air matanya mengalir deras ke pipinya, terisak. Seluruh tubuhnya gemetar, ia takut, ngeri. Tetapi wanita itu justru tambah menyeringai puas. Mulutnya tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan hanya untuk membela diri.
"Ohh ... cup cup cup ... jangan menangis," perempuan itu memeluk tubuh putrinya yang kini tersedu. Mengelus rambut hitamnya yang berantakan. "Gadis cantik tidak boleh menangis. Jangan takut, rasanya enak kok, kau pasti akan suka. Nanti kau juga bisa dapat uang banyak," bisiknya sambil tertawa pelan.
Itu tiga tahun lalu. Tiga tahun. Itulah memori yang ia miliki jika seseorang menyebut kata 'orang tua'.
Uang, hidup enak, laki-laki. Bagi wanita itu, dengan wajah ini saja sudah cukup. Dengan tubuh ini saja sudah cukup.
Kini ia berada di sebuah jet mewah bersama dengan rekan satu timnya. Pemuda itu bahkan baru saja mewarisi perusahaan keluarga berskala besar.
Aleksei ... juga laki-laki kan?
"Si brengsek itu ...," gumamnya. Tangannya mengepal erat hingga terlihat sangat pejal. "Mau bikin aku jadi bahan olok-olok disana?!" mata birunya ia jatuhkan ke angin kosong di sebelah kirinya.
Gadis di depannya masih melipat kakinya yang jenjang terbungkus rok span pendek seragam kampus Andromeda. Pertama kali melihat pemuda itu semarah ini. Lebih marah daripada saat Gilbert berbohong padanya agar bisa bolos latihan beberapa hari sebelum turnamen.
"Katakan padaku, Lin. Orang tolol mana yang meminta anak kuliahan untuk jadi presdir?" tanyanya tajam sambil mengetuk-ketukkan telunjuk ke pelipis kanannya. Kini pemuda itu menatap Lin lekat-lekat, seolah meminta untuk berada di pihaknya. Namun gadis itu hanya diam.
Tubuh Aleksei membungkuk ke depan. Kedua sikunya telah bertumpu pada kedua pahanya. Kini tangan pemuda itu dua-duanya sudah memegangi dahi, menyibak sebagian rambut coklatnya hingga beberapa helai berada di sela-sela jari-jarinya. Ia tertunduk dalam. Matanya terpejam erat. "Presdir, Lin! Presiden direktur!" pekiknya.
Giginya mengatup erat seraya menggeram. "AAAKH! Brengsek!" Tangannya meremas rambut-rambut tak bersalah di kepalanya. Kali ini ia berteriak dengan mengabiskan seluruh nafas yang ada di paru-parunya. Hingga menutupi suara deruan mesin jet.
Ia melempar tubuhnya bersandar di sofa tunggal yang empuk. Matanya kembali terpejam ditemani jari-jarinya yang sudah memijit kedua rongga mata di dekat pangkal tulang hidung. Ia menarik nafas panjang berusaha menenangkan dirinya yang barusan terengah.
"Kenapa harus aku?" lirihnya. Mereka hening beberapa saat. Hanya suara lembut mesin jet yang memenuhi suasana itu. Lin sedari tadi hanya memangku kedua tangannya sambil menatapi laki-laki yang emosinya sedang membuncah. Ia menelan ludah.
"Bukankah karena kau anaknya?" tanya gadis itu pelan.
Pemuda itu berdecak geli. Ia memiringkan senyumnya dengan sinis. "Si brengsek itu sudah tidak punya anak," tukasnya dingin. "Dia sebut dirinya ayah? Pengkhianat menjijikan itu ... selalu semaunya sendiri," cibirnya. Kedua tangannya bersedekap di depan dada bidangnya.
Lin menggaruk tengkuknya sedikit. Ia tak yakin bagaimana menenangkan kaptennya. Apalagi ini adalah soal 'ayah', bidang yang sangat tidak dikuasai olehnya. Tahu apa dia soal seorang ayah?
"Tapi bukankah kau sudah pernah terlibat proyek perusahaan ayahmu, Kapten?" tanyanya lagi.
Aleksei menghela pelan. "Proyek anak bawang maksudmu?" pemuda itu malah balik bertanya. Wajahnya justru menjadi lebih sebal daripada sebelumnya. Lin tak bisa berkata yang lain-lain.
"Kalau ibuku masih hidup, si brengsek itu tidak akan begini," ketusnya. "Di otaknya cuma ada uang dan uang. Aku berusaha mati-matian agar bisa lulus dari akademi lebih cepat. Kupikir akhirnya aku pulang, tapi ternyata aku hanya serumah dengan orang brengsek! Orang bejat!" wajahnya menatap jendela yang mulai menghitam pemandangannya. Ia memukulkan kepalan tangannya pada sandaran lengan yang tak bersalah.
"Sekarang dia baru menganggapku anak ketika dia bisa memakaiku sebagai bidak. Ya. Itu benar. Aku hanya bidak untuk mengurusi sumber uangnya yang lain," cecarnya. "Tidak lebih dari itu!"
Ketika umur enam hingga tujuh tahun, anak-anak yang memiliki Ziel seperti dirinya dan Aleksei akan langsung dimasukkan ke akademi. Sekolah asrama khusus pemilik Ziel.
Anak-anak akan sangat jauh dari orang tua. Biasanya akademi ini letaknya akan jauh dari lingkungan masyarakat biasa. Seseorang akan dianggap lulus dari akademi ketika dianggap sudah memiliki kematangan dalam mengendalikan Ziel-nya. Dimana artinya tidak menggunakan Ziel secara serampangan. Mereka hanya bisa bertemu keluarga selama seminggu ketika libur musim panas. Setelah lulus pun segala identitas mereka akan dipermak sedemikian rupa hingga pada level data cloud.
Cloud, sebuah sistem yang menyimpan seluruh data pribadi maupun publik secara maya, layaknya internet di jaman dulu. Data yang dipermak itu memungkinkan pemilik Ziel tidak terdeteksi, dan akan dianggap sebagai warga biasa, dengan catatan mereka tidak menunjukkannya kekuatannya di publik. Bahasa kasarnya adalah dengan menyembunyikan kehadiran mereka dalam masyarakat. Keamanan data pemilik Ziel sangat dilindungi oleh biro.
"Pengkhianat ...," gumamnya sambil kembali mengepalkan tangan hingga buku-bukunya terlihat. Matanya sudah memicing tajam menatap jendela. Sudah membara.
"Kau benci ayahmu?"
Pemuda itu tersentak.
Benci?
Ia merenung, semburat keraguan muncul di wajahnya yang tampan itu. Perlahan tatapan bengis itu berubah menjadi sendu. Bola matanya melirik ke arah lain. Wajahnya kini getir.
"Maaf. Seharusnya ... aku tak beri tahu masalah pribadi begini," ia berujar dengan pelan. Mereka berdua diam membisu. Aleksei menenangkan dirinya. Ia menyesap air dari gelas yang baru ia sentuh setelah setengah jam diam di tempat gelas sofa tunggalnya.
Tiba-tiba Lin melihat situasi yang familiar baginya. Perasaan itu. Ekspresi itu. Gadis itu paham.
Ia menarik nafas dalam-dalam, membetulkan posisi duduknya sekaligus menegakkan tubuhnya. Sebuah senyum kecil ia sunggingkan meskipun tahu pemuda itu tak akan terlalu peduli.
"Kapten, ada pepatah berbunyi, 'Tidak ada kemuliaan di dalam kemiskinan'. Alasanku bergabung di tim ini adalah untuk mendapatkan uang. Hanya itu yang aku inginkan." Pemuda itu menaikkan sebelah alisnya. Penasaran mengapa tiba-tiba gadis itu berkata demikian. Aleksei khidmat mendengarkan. Tubuhnya masih bersandar nyaman.
"Hanya uang, Kapten. Hanya uang," ulangnya dengan tatapan mantap. "Tapi ...," imbuhnya.
Mata gadis itu terlihat bersinar. Senyumnya kali ini memancarkan aura positif yang berbeda. "Aku mendapatkan lebih dari uang di tim ini." Kedua alis Aleksei berkait, ia menelengkan kepalanya ke kiri dengan penasaran.
"Keluarga," ucapnya sambil berbinar.
"Pfft!" Membuat Aleksei justru tersenyum geli hingga membuat bahunya sedikit bergetar. Klise dan dangkal sekali pikirnya. Menganggap Lin seperti anak kecil yang sedang hidup di dunia imajinasi dengan pulau kapuk dan sungai dari susu stroberi. Tawanya itu agak menghina.
Melihat pemuda itu malah terlihat menertawakannya seolah diremehkan, ia tidak terima. Dahinya mengernyit, senyumannya padam. Mata hitamnya sudah menatap tidak suka pada Aleksei.
"Kapten, apa itu keluarga?" seketika itu senyum di bibir Aleksei redup.
"Keluarga ... keluarga adalah ...," bibirnya terbata-bata. Ia pikir ia bisa menjelaskannya.
Mulutnya sudah agak terbuka seolah ingin memuntahkan kalimat berikutnya, namun nihil. Kemampuannya hanya sampai di situ saja. Gadis itu menancapkan pandangannya pada mata biru terang Aleksei. Pemuda itu menyerah, ia tak lagi berani beradu tatap dengan Lin, mulutnya terkunci mantap.
Dadanya terasa sesak. Jutaan memori indah sekaligus pahitnya terpanggil seluruhnya di dalam kepala. Tangannya mengepal. Pilu saat harus menjelaskan kata itu. Kata yang baginya kini sudah menjadi barang mewah. Ia berusaha begitu keras menahan air matanya layaknya seorang pria. Pemuda itu tertunduk dalam. Tatapannya jatuh ke pangkuannya yang kosong.
Itu benar. Aku yang dulu muak dengan kata itu. Aku yang dulu selalu mencibir kata itu. Aku yang dulu membencinya. Kini aku sedang melihatmu, persis seperti aku yang dulu. Diriku yang hancur.
Kali ini Lin tersenyum menang. Menang dari tawa kecil pemuda itu. Namun tak ada perasaan senang sedikit pun dari kemenangannya. Justru nyeri di ulu hatinya.
"Keluarga bukan cuma perkara kau sedarah dengan siapa, tetapi juga soal kau mau berdarah untuk siapa," jelas Lin.
Pemuda itu mendongak seketika mendengarnya. Mungkin itu kata-kata yang ingin sekali ia ucapkan, namun tak satu patah pun keluar dari bibir tipisnya. Bahkan baginya, jawaban Lin jauh lebih baik dari miliknya.
"Aku juga sepertimu dulu. Datang. Latihan. Rapat. Turnamen. Pulang. Lalu dapat uang. Persetan dengan yang lain-lain," mata gadis itu menyapu interior langit-langit jet baru Aleksei.
Tangan kirinya bertumpu pada sandaran tangan sofa tunggal sambil memangku dagunya. "Tetapi Ginger dan Nona Prim sangat baik padaku. Gilbert dan Manajer Simone juga," imbuhnya sambil tersenyum-senyum sendiri.
Ia melemparkan kembali pandangannya pada sang kapten. Wajah pemuda itu sedang terkesima, sekaligus terlihat pedih.
"Mungkin bagimu berbincang-bincang hal pribadi begini melewati batas, terlalu personal. Tetapi ketika menikmatinya, sama sekali tidak," ia menatap kaptennya dengan masih memangku dagunya. "Kau selalu membuat jarak dengan kami. Selalu memisahkan pekerjaan dengan pribadi. Tidak harus seperti itu, Kapten."
Sejujurnya aku cuma membuat jarak denganmu saja, Lin, batinnya.
Pemuda itu membisu. Lin menunggu-nunggu respon Aleksei hingga ia menggoyang-goyangkan pergelangan kakinya yang menggantung. Tidak ada.
"Kalau Kapten segusar ini, kenapa tidak coba menghubungiku saja? Sekedar cerita kan tidak apa-apa," ucapnya lagi.
Sejujurnya jika soal perkara ingin menghubungi gadis itu, ia sudah ingin melakukannya berkali-kali. Saat malam ia kalut dalam kesendiriannya di atas tempat tidur, ia berulang kali hampir menghubungi Lin. Hanya ingin sekedar bertanya apa kabar, ia bahkan belum sempat menyampaikan ucapan selamat semenjak gadis itu diterima di kampus paling beken di planet ini.
Setiap kali rasa kesepian itu datang, dan keinginannya ingin menghubungi Lin timbul, berkali-kali ia urungkan.
Kesempatan itu datang pagi ini, ketika ia tiba-tiba terbangun oleh panggilan Simone untuk datang ke kantor. Namun pemuda itu kikuk. Ia membabi buta akun cloud Lin, melakukan panggilan berkali-kali. Yang sebelumnya ia khawatir dengan asumsi Lin sedang sibuk, pagi ini malah membombardir panggilan tanpa peduli apa yang gadis itu lakukan. Setelah panggilan diangkat pun ia begitu bodoh tak sempat memakai pakaian yang sopan. Mengingat itu wajahnya agak memanas. Memalukan.
Cukup lama mereka hening. Lin dari tadi menunggu umpan balik pemuda itu, namun kini justru ia tidak di gubris. Ia menarik nafas panjang lalu tersenyum kecil. Gadis itu bangkit dari sofa tunggal yang empuk. Berdiri di atas sepatu hak tingginya. Kedua tangannya terbuka, menawarkan Aleksei untuk datang padanya.
"Kemarilah," Aleksei mendongak, mata mereka bertemu. Tatapan mata gadis itu begitu hangat dan lembut. Aleksei tak yakin bagaimana ekspresi wajahnya sekarang. Ia ragu-ragu berdiri berhadapan dengan gadis itu tanpa sejenak pun melepas tatapan mereka.
ns 15.158.61.8da2