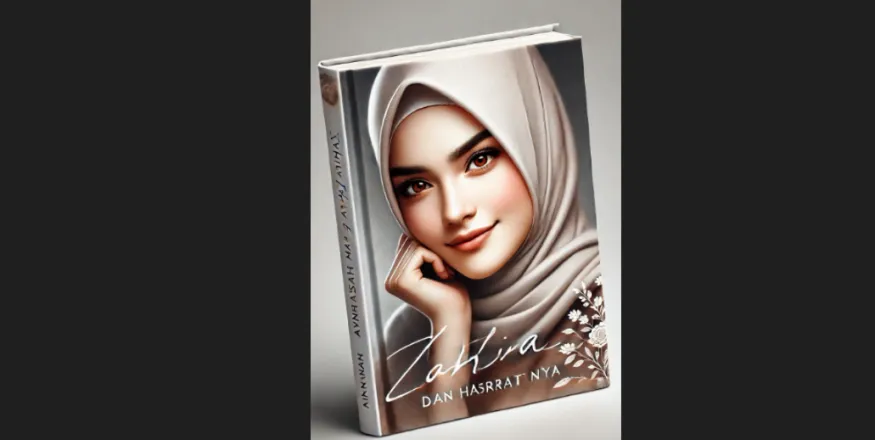x
x
Chapter 6
Sinar mentari senja mengintip dari balik tirai ketika suara ketukan familiar terdengar dari pintu depan.
“Assalamualaikum…” Terdengar suara salam.
“Waalaikumsalam.” Aku membuka pintu.
Tiwi, dengan senyum hangatnya yang khas, kembali hadir membawa secercah kehangatan di sore yang temaram. Seperti biasa, dia membawa sebungkus kue dari toko favoritnya - sebuah kebiasaan kecil yang selalu dia lakukan setiap berkunjung.
Kami duduk di beranda belakang, ditemani secangkir teh hangat dan hembusan angin sore yang menyejukkan. Obrolan mengalir ringan seperti biasa, membahas hal-hal sederhana tentang keseharian, hingga tiba-tiba Tiwi mengubah raut wajahnya menjadi lebih serius. Jemarinya memainkan ujung cangkir dengan gelisah.
"Ada yang ingin kuceritakan padamu," ujarnya pelan, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. "Ini tentang Bram."
Mendengar nama itu, jantungku seakan berhenti berdetak untuk sesaat. Nama yang selama ini kucoba kubur dalam-dalam, kini kembali mengusik ketenangan yang sudah susah payah kubangun. Tiwi dan Rachel , sahabat terbaikku sejak SMA, adalah dua orang sahabat dekat yang tahu detail kisahku dengan Bram - sebuah cerita yang kini tersimpan rapi dalam sudut memori yang paling dalam.
"Kemarin aku tidak sengaja bertemu dengannya di mall," lanjut Tiwi, matanya mengawasi reaksiku dengan seksama. "Dia tampak berbeda, tapi tetap... Bram yang dulu."
Angin sore berhembus lebih kencang, menerbangkan beberapa helai daun kering di halaman. Seperti daun-daun itu, pikiranku pun berkelana, melayang ke tempat-tempat yang sudah lama tidak kukunjungi dalam ingatan. Tiwi masih berbicara, tapi suaranya terdengar samar, bercampur dengan gemerisik daun dan detak jantungku sendiri yang semakin keras.
"Dia menanyakan kabarmu," Tiwi melanjutkan dengan hati-hati.
“Terus kamu bilang apa ke dia.” Sahut aku mencoba tenang.
“Aku bilang aja lupakan Zahira dia sudah bahagia dengan suaminya sekarang.”
“Makasih kamu udah ngomong gitu, terus dia gimana?”
“Dia kayak gak terima gitu dan pengen balas apa yang kamu lakukan dengan hancurin rumah tangga kamu.”
Aku agak bingung mendengar apa yang dikatakan oleh Tiwi. Sebab beda dengan yang aku dengar dari Rachel. Tapi tak urung ada perasaan kecewa mendengar Bram punya keinginan jahat seperti itu.
Cangkir teh di tanganku terasa dingin sekarang. Sore yang tadinya tenang kini dipenuhi berbagai pertanyaan yang berkecamuk.
Tiwi menggenggam tanganku lembut, seolah mengerti badai yang tengah bergejolak dalam hatiku. "Kamu tidak perlu memikirkannya terlalu dalam," bisiknya menenangkan. "Aku hanya merasa kamu perlu tahu dan hati-hati dengan Bram."
Senja semakin tenggelam, menyisakan semburat jingga yang perlahan memudar di langit. Percakapan kami berhenti karena beberapa saat lagi mau masuk waktu magrib. Ketika Tiwi akhirnya pamit pulang, aku berdiri di depan pintu, menatap sosoknya yang menghilang di kegelapan malam. Informasi yang dia bawa hari ini makin menguatkan aku untuk melupakan Bram.
***
Rembulan bersinar lembut melalui jendela kamar ketika aku dan Haris berbaring bersama, menjalani ritual malam kami yang sudah menjadi kebiasaan. Lampu tidur menyala redup, menciptakan suasana intim yang menenangkan. Seperti biasa, kami berbagi cerita tentang hari yang telah dilalui, menciptakan momen kebersamaan yang seharusnya terasa sempurna.
"Bagaimana presentasimu hari ini?" tanyaku, mengawali percakapan sambil memiringkan badan menghadapnya.
Haris tersenyum, matanya berbinar ketika mulai bercerita. "Berjalan lancar. Tim sangat menyukai konsep baru yang kuajukan. Minggu depan kami akan mulai implementasinya." Dia menjelaskan dengan antusias tentang proyeknya, sesekali tangannya bergerak-gerak menggambarkan idenya.
"Kamu memang selalu punya ide-ide brilian," pujiku tulus. Memang benar, Haris selalu cemerlang dalam pekerjaannya.
"Bagaimana denganmu? Kulihat tadi sore ada temanmu berkunjung?" tanyanya dengan nada penuh perhatian.
Untuk sesaat, hatiku mencelos mengingat pembicaraan dengan Tiwi tentang Bram. "Oh, iya. Tiwi mampir sebentar. Dia membawakan kue kesukaanku."
Haris mengangguk. "Tiwi memang sahabat yang perhatian. Kamu beruntung memiliki teman seperti dia."
Percakapan berlanjut ke rencana akhir pekan. Haris mengusulkan untuk mengunjungi sebuah kafe baru di pusat kota. "Katanya coffee art-nya unik. Kamu pasti suka," ujarnya penuh semangat.
"Kedengarannya menyenangkan," jawabku, berusaha terdengar antusias meski pikiran masih mengembara.
Kami juga membahas rencana liburan akhir tahun. Haris ingin mengajakku ke Bali, tempat yang selalu ingin kukunjungi. Dia bahkan sudah mencari-cari villa yang cocok dengan selera kita berdua.
"Kita bisa melihat matahari terbit di Sanur," katanya sambil membelai rambutku lembut. "Atau surfing di Kuta, kalau kamu berani."
Semuanya terdengar sempurna. Haris selalu tahu cara membuatku tersenyum, selalu berusaha memenuhi keinginanku bahkan sebelum aku mengutarakannya. Dia adalah suami yang begitu perhatian, begitu pengertian.
Tapi entah mengapa, malam ini jarak di antara kami terasa lebih nyata dari biasanya. Meski tubuh kami hanya terpisah beberapa sentimeter, ada jurang tak kasat mata yang seolah memisahkan kami. Setiap kata yang terucap, setiap sentuhan yang terasa, semua seakan melewati dinding tebal yang tak mampu kuruntuhkan.
"Kamu lelah?" tanya Haris lembut, menyadari keheningan yang mulai menyelimuti.
"Sedikit," jawabku, bersyukur memiliki alasan untuk mengakhiri percakapan.
Setelah percakapan usai, Haris mendekatiku, seperti biasa. Dia mencium keningku dengan lembut, lalu perlahan merangkul tubuhku. Aku membiarkannya, mencoba untuk merespons dengan cara yang dia harapkan. Tapi, seperti malam-malam sebelumnya, aku tidak bisa merasakan keintiman yang seharusnya ada antara suami dan istri. Semuanya terasa begitu hambar, seperti rutinitas yang harus kami jalani.
Aku mencoba untuk terlibat, mencoba untuk merasakan apa yang seharusnya aku rasakan. Tapi, semakin aku berusaha, semakin aku merasa kosong. Aku tidak bisa merasakan getaran, tidak bisa merasakan hasrat yang seharusnya muncul. Semuanya terasa begitu mekanis, seperti kami hanya menjalankan kewajiban, bukan menikmati momen bersama.
Haris tidak pernah protes atau mengeluh. Dia selalu berusaha membuatku nyaman, dan aku tahu dia mencintai aku sepenuh hati. Tapi, semakin dia berusaha, semakin aku merasa bersalah. Aku tahu aku tidak bisa memberinya apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Aku tidak bisa memberinya cinta yang tulus, karena hatiku masih terbelenggu oleh kenangan masa lalu.
Kami bersetubuh dengan hanya melepas celana dalam dan tetap ada pakaian yang menutupi sebagian tubuh kami. Beberapa pompaan kontolnya di memek aku dan ketika aku mulai merasa birahi mulai muncul saat itulah Haris sudah berjuang menahan orgasmenya dan dia tidak mampu.
Setelah semuanya selesai, Haris tertidur dengan tenang, sementara aku berbaring di sampingnya, memandang langit-langit kamar. Aku merasa seperti sedang menjalani kehidupan yang bukan milikku, seperti sedang memainkan peran dalam sebuah drama, bukan menjalani kehidupan nyata. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus menjalani pernikahan yang terasa begitu hambar, sementara hatiku masih terikat pada kenangan masa lalu.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba untuk menenangkan diri. Aku tahu aku harus membuat keputusan, meskipun itu berarti aku harus menghadapi ketidakpastian dan rasa sakit yang mungkin akan datang.
208Please respect copyright.PENANAFbqgnBmo7d
***
Besok, Haris akan melakukan perjalanan dinas keluar kota selama seminggu. Seperti biasa, aku memutuskan untuk menginap di rumah orang tuaku karena aku tidak nyaman tinggal sendirian di rumah. Malam ini, suasana terasa berbeda. Udara malam yang biasanya tenang, seakan membawa beban yang lebih berat.
"Sudah siap dengan semua yang mau dibawa, Mas?" tanyaku sambil memastikan tasnya sudah terpacking rapi.
"Sudah, Sayang. Jangan khawatir," jawab Haris dengan senyum lembut. Dia mendekat, memelukku erat, dan mengecup keningku dengan penuh kelembutan. "Kamu jaga diri baik-baik, ya. Jangan lupa makan teratur dan kalau ada apa-apa, langsung telepon aku."
Aku mengangguk, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk di hatiku. Matanya yang teduh memancarkan kasih sayang yang tulus, membuatku merasa bersalah karena tak bisa membalas cintanya sepenuh hati seperti yang dia berikan padaku.
***
Malam itu, setelah kepergian Haris, suasana rumah orang tuaku terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku mencoba mengisi waktu dengan membuka ponsel melihat-lihat media sosial. Tapi pikiran terus melayang ke apa yang di katakan Tiwi soal Bram dan juga apa yang dikatakan Rachel juga soal Bram.
Saat aku sedang bersiap untuk tidur, tiba-tiba teleponku berdering. Aku mengira itu Haris, mungkin ingin memberi kabar bahwa dia sudah sampai dengan selamat. Tapi saat aku melihat layar ponselku, jantungku berdegup kencang. Nama "Bram" muncul dengan jelas di layar. Sudah beberapa harir dia tidak menghubungiku, dan tiba-tiba dia menelpon. Aku ragu sejenak, tangan gemetar memegang ponsel. Haruskah aku mengangkatnya? Apa yang dia inginkan?
Akhirnya, dengan napas berat, aku mengangkat telepon itu. "Halo?" suaraku terdengar ragu.
“Zahira,” suara Bram terdengar lembut, tapi penuh arti. “Aku… aku tahu ini tiba-tiba. Tapi, bisakah kita bertemu?”
Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. “Bram kita kan sudah ketemu dan itu cukup. Jadi aku rasa tidak ada lagi alasan bagi aku untuk ketemu kamu.”
“Kenapa gitu, Zahira?” katanya, suaranya terdengar sedih. “Apa kamu gak mau beri kesempatan aku melepas rindu sebagai mantan kekasih. Aku hanya ingin bertemu. Sekali lagi. Aku masih punya banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu.”
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. “Bram, ini gak baik buat aku dan juga buat kamu. Kita sudah punya hidup masing-masing sekarang.”
“Zahira, tolong,” suaranya terdengar memohon. “Aku tidak meminta banyak. Hanya satu pertemuan. Aku hanya ingin melihatmu, ingin tahu bagaimana kabarmu.”
Aku merasa hati meleleh mendengar nada suaranya. Aku tahu ini salah, tapi ada bagian dari diriku yang tidak bisa menolak. “Bram, aku… aku tidak tahu.”
“Zahira, aku masih mencintaimu,” katanya tiba-tiba, membuatku tertegun. “Aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku tahu ini rumit, tapi tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan.”
Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. “Bram, ini tidak adil. Aku sudah menikah. Aku punya tanggung jawab.”
“Aku tahu, Zahira. Tapi, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang belum selesai. Aku hanya ingin bertemu, hanya sekali saja.”
Aku menutup mata, mencoba untuk berpikir jernih. Tapi, semakin aku mencoba, semakin aku merasa terjebak. “Bram, aku… aku tidak bisa janji apa-apa. Tapi, aku akan memikirkannya.”
“Terima kasih, Zahira,” katanya, suaranya terdengar lega. “Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih peduli padamu. Aku masih memikirkanmu.”
Aku mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. “Aku tahu, Bram. Tapi, tolong beri aku waktu.”
“Aku akan memberimu waktu, Zahira. Tapi, tolong jangan lupakan satu hal: aku masih mencintaimu, dan aku akan selalu ada untukmu.”
Aku menutup telepon itu dengan hati yang berat. Aku tahu ini adalah kesalahan besar, tapi ada bagian dari diriku yang tidak bisa menolak. Aku terjebak di antara dua dunia: satu yang sudah aku pilih, dan satu lagi yang tidak pernah benar-benar pergi dari hatiku.
Aku memohon petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apa pun yang akan terjadi. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tapi aku percaya bahwa dengan pertolongan-Nya, aku akan menemukan jawaban yang benar. Dan, pada akhirnya, aku hanya bisa berharap bahwa apapun keputusan yang aku buat, itu akan membawa kebahagiaan dan kedamaian untuk semua orang yang terlibat.
208Please respect copyright.PENANAGJ2xmx80DQ
Bersambung
ns 15.158.61.16da2