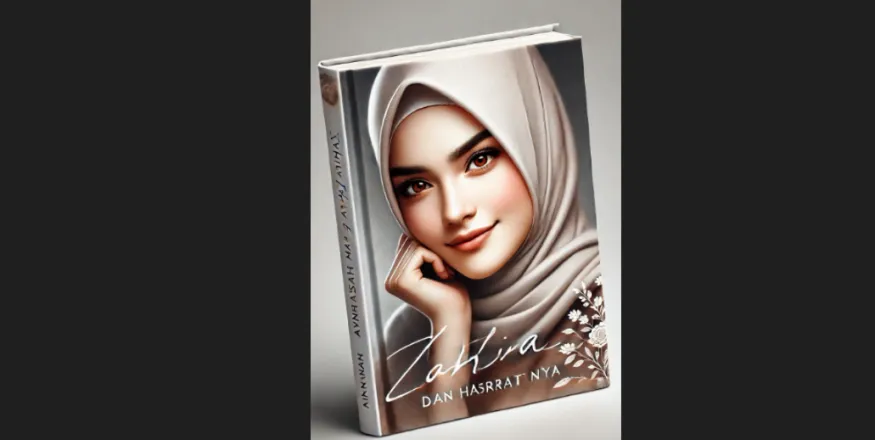x
x
Chapter 7
Sore itu, kamarku diterangi cahaya jingga yang menyelinap lewat celah tirai. Udara terasa tenang, hingga suara "ding" dari ponselku memecah kesunyian. Aku mengangkatnya, dan nama Bram muncul di layar. Pesan singkat itu membuat dadaku berdebar.
"Zahira, apa kamu udah siap buat ketemuan? Kamu kan bilang kemarin masih memikirkannya. Gimana, sudah ada keputusan?" tanya Bram lewan pesannya.
Aku menatap pesan itu lama, jemariku menggantung di atas layar. Sudah beberapa hari aku menghindari pertanyaan ini, tapi sekarang, aku tahu jawabannya. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu mengetik balasan dengan hati-hati.
"Bram, aku sudah memikirkan semuanya. Aku rasa ini yang terbaik untuk kita berdua. Aku memutuskan untuk tidak bertemu lagi denganmu." Balas aku dengan tegas.
Pesan itu terkirim, dan aku menaruh ponselku di sampingku. Tapi tak sampai sepuluh detik, ponsel itu bergetar lagi. Aku menghela napas sebelum membacanya.
4107Please respect copyright.PENANAvjygTlA5E8
"Kenapa kamu setega itu Zahira? Apa ada yang salah kalau aku ingin semua dibicarakan lagi sampai tuntas? Kita kan bisa bicara baik-baik. Aku pikir kita masih bisa menyelesaikan ini." Bram sepertinya tidak menyerah.
Aku mengerutkan kening. Kata-katanya membuat hatiku sedikit goyah, tapi aku tahu ini bukan tentang menyelesaikan sesuatu. Ini tentang apa yang terbaik untukku. Aku mengetik lagi, kali ini lebih tegas.
"Bram, ini sudah selesai saat aku memilih menikah dengan Haris. Jadi tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan."
Kali ini, Bram tidak langsung membalas. Aku membayangkan dia sedang duduk di sana, mungkin menatap layar ponselnya dengan ekspresi bingung atau kecewa. Tapi aku tak bisa membiarkan diriku terbawa perasaan. Ini adalah keputusan yang sudah kupertimbangkan matang-matang.
Beberapa menit berlalu, dan ponselku bergetar lagi. Aku mengambilnya, membaca pesan baru dari Bram.
"Aku mengerti, tapi aku masih berharap kita bisa bertemu. Setidaknya sekali lagi."
Aku menatap layar ponselku, mencoba menahan gejolak emosi yang tiba-tiba muncul. Aku tahu, jika aku menyerah sekarang, semua keputusan yang sudah kuambil akan sia-sia. Aku mengetik balasan dengan hati-hati, memastikan setiap kata yang kutulis mencerminkan ketegasanku.
"Bram, aku tahu ini sulit. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harap kamu bisa menghormati keputusanku. Terima kasih untuk semua kenangan indah yang pernah kita bagi, tapi ini adalah akhir dari cerita kita."
Setelah mengirim pesan itu, aku mematikan ponselku. Aku tak ingin tergoda untuk membalas jika dia mengirim pesan lagi. Aku menatap langit jingga di luar jendela, mencoba menenangkan diri. Keputusan ini berat, tapi aku tahu ini yang terbaik.
Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Rasanya seperti beban berat yang selama ini kupikul perlahan terlepas. Ini adalah awal baru untukku, dan aku siap menghadapinya.
****
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. "Ini untuk kebaikanmu sendiri," bisik hatiku. Tapi bisikan itu seolah tenggelam dalam lautan keraguan yang menggelora. Aku tahu Bram. Dia takkan berhenti mencoba. Dia akan terus mengirim pesan, menelepon, merayuku dengan kata-kata manis yang dulu selalu berhasil membuatku luluh. Dan aku? Aku tak yakin bisa bertahan.
Dengan hati yang berat, aku membuka pengaturan ponselku. Jari-jariku bergerak dengan gemetar, tapi tekadku sudah bulat. Aku memblokir nomor Bram. Aku memastikan bahwa dia tak akan bisa menghubungiku lagi. Aku tak mau memberi kesempatan pada mantanku itu untuk mendekati aku lagi, bahkan kesempatan sekecil apa pun.
Setelah semuanya selesai, aku meletakkan ponselku di atas meja. Rasanya seperti melepaskan sesuatu yang sangat berharga, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Aku tak bisa terus terjebak dalam hubungan yang hanya membuatku terluka. Aku harus melindungi diriku sendiri, meski itu berarti harus melukai Bram.
Tapi kenapa rasanya begitu sakit?
Aku menutup mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku ingat semua kenangan indah yang pernah kami bagi. Tawa, pelukan, dan janji-janji yang dulu terasa begitu nyata. Tapi sekarang, semua itu hanya menjadi bayangan yang mengikuti langkahku, mengingatkanku pada sesuatu yang tak bisa kupertahankan.
Ponselku bergetar lagi, dan hatiku berdebar kencang. Aku tahu itu bukan Bram—nomornya sudah kublokir—tapi tetap saja, suara itu membuatku tersentak. Aku mengangkatnya, dan melihat pesan dari sahabatku, Tiwi.
"Gimana Za, Bram masih menghubungi kamu?" tanya Tiwi.
Tiwi selalu ada untukku, bahkan di saat-saat seperti ini. Aku mengetik balasan, mencoba meyakinkannya—dan juga diriku sendiri—bahwa aku baik-baik saja.
"Iya tadi. Tapi aku tegas menolak keinginan dia. Terus aku blokir nomornya. Aku harus melakukan ini, Tiwi. Aku tak bisa terus begini."
Beberapa detik kemudian, ponselku bergetar lagi.
"Aku mendukung kamu Za. Emang harus kayak gitu. Jangan beri peluang sekecil apapun buat dia. Apalagi dia pernah punya niat tidak baik sama kamu."
Aku menghela napas, merasa sedikit lega. Tapi rasa sakit itu masih ada, menggerogoti hatiku pelan-pelan. Aku tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Ini hanya awal dari proses yang mungkin akan lebih panjang dan lebih berat. Tapi aku harus kuat. Aku harus bertahan.
Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandangi langit yang mulai gelap. Bintang-bintang kecil mulai bermunculan, seolah memberi tanda bahwa malam akan segera tiba. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri.
"Ini untuk kebaikanmu," bisikku pada diriku sendiri. "Kamu harus melangkah maju."
Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang bertanya, "Apa aku bisa?"
Aku tak tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti: aku tak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Aku harus mencoba, meski itu berarti harus melukai diriku sendiri dan Bram.
Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega, tapi juga ada rasa sakit yang tak bisa kuhilangkan. Tapi aku tahu, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Dan meski jalan di depanku masih panjang, aku akan mencoba untuk tetap kuat.
***
Ponselku bergetar di tengah keheningan sore. Aku lihat nama yang tertera di layar. Tenyata Rachel, segera aku terima panggilan teleponn itu.
"Hallo Za," Sapa Rachel
“Hallo juga Rachel.” Jawabku,
"Gimana kabar kamu Za?"
“Alhamdulillah baik Chel.”
“ Sorry ya Za. Bram ada di sini sama aku. Dia pengen bicara." Ucap Rachel seperti agak ragu.
Tubuhku menegang. Setelah aku blokir ternyata dia masih berusaha untuk bisa bicara dengan aku. Aku bukannya takut bicara dengan Bram, tapi aku takut pada perasaanku sendiri.
"Rachel, maaf ya aku gak bisa, kamu pasti ngerti kan. Karena kamu juga udah nikah kayak aku." bisikku lirih, berusaha mengendalikan degup jantung yang mendadak tak beraturan.
"Iya, aku tahu. Tapi Bram bilang ini penting. Hanya sebentar..."
Kupejamkan mata, mengucap istighfar dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Kenapa di saat aku sedang berjuang menjadi istri yang baik, masa lalu harus kembali mengetuk?
"Maaf Rachel, sampaikan pada Bram bahwa aku tidak bisa," jawabku tegas meski ada getir yang terasa. "Aku sudah memilih jalanku. Dan berbicara dengan mantan kekasih... itu tidak baik untuk rumah tanggaku."
"Tapi Za..."
"Rachel," potongku lembut. "Tolong mengertilah. Mungkin dulu aku dan Bram punya cerita, tapi sekarang aku punya kewajiban pada suamiku. Aku tidak mau mengkhianati kepercayaan Haris."
Kudengar helaan napas panjang dari seberang. "Oke, aku mengerti. Sorry ya Za. Aku cuma pengen nolong Bram yang kayaknya kacau banget gak bisa ngehubungi kamu."
“Sampaikan saja sama dia aku minta maaf dan minta dia untuk move on.”
Setelah menutup telepon, aku terduduk di tepi ranjang. Air mata yang kutahan akhirnya menetes. Aku tak bisa memungkiri masih ada ruang untuk Bram yang belum sepenuhnya tertutup. Aku berusaha keras untuk bisa menutupnya dan itu tentu dengan menyakiti Bram.
"Ya Allah, kuatkan aku," bisikku sambil mengusap air mata. "Jadikan aku istri yang setia, dan gantikan sisa perasaan ini dengan cinta yang lebih besar untuk Haris."
Kupandangi foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Haris yang selalu sabar dan pengertian, yang mencintaiku dengan tulus meski tahu aku pernah memiliki masa lalu. Tidak, aku tidak boleh mengkhianati kepercayaannya. Bram mungkin bagian dari masa laluku, tapi Haris adalah pilihan masa depanku.
Kuambil wudhu dan menunaikan shalat, memohon pada Allah agar menguatkan hatiku, dan membantuku menjadi istri yang lebih baik lagi untuk Haris.
***
Sebulan sudah berlalu sejak kuputuskan memblokir nomor Bram. Keputusan yang kuambil demi menjaga rumah tangga aku. Karena aku tak yakin bahwa aku mampu menolak pesona Bram bila terus memberi kesempatan dia mendekati aku.
Tapi seperti kutukan, semakin kucoba menghapus jejaknya, bayangan Bram justru semakin lekat dalam benakku. Sementara itu, kehidupan rumah tanggaku dengan Haris berjalan seperti air yang menggenang. Tenang, tapi membosankan. Tidak ada riak, tidak ada gelombang yang membuat jantung berdebar. Hanya rutinitas yang sama, hari demi hari. Sarapan dengan obrolan yang boleh dibilang terlalu formal bagi sepasang suami istri, lambaian tangan hampa saat dia berangkat kerja, dan makan malam yang diisi percakapan layaknya dua orang yang tidak begitu dekat.
Tiga tahun pernikahan tanpa kehadiran anak semakin menambah kekosongan di antara kami. Di malam-malam sepi, saat Haris sudah terlelap, pikiranku sering melayang pada Bram. Pada tawa renyahnya yang menular, pada cara dia memandangku seolah aku adalah harta paling berharga di dunia. Pada mimpi-mimpi yang dulu kami rajut bersama saat menjalin hubungan sebagai kekasih. Mimpi yang kini hanya bisa kusimpan dalam kotak kenangan.
Aku merasa berdosa setiap kali membandingkan Haris dengan Bram. Suamiku itu lelaki baik - terlalu baik malah. Dia tidak pernah menuntut apa-apa dariku, selalu sabar menghadapi mood-ku yang naik turun, dan berusaha keras membuatku bahagia dengan caranya sendiri. Tapi mengapa hatiku masih sering memberontak? Mengapa bayang-bayang Bram masih sering menghantuiku?
Setiap pagi, saat bercermin, aku melihat lingkaran hitam di bawah mataku semakin jelas. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena beban pikiran yang semakin berat. Pertanyaan-pertanyaan mulai menggerogoti batinku: Sampai kapan aku harus bertahan dalam pernikahan yang terasa hambar ini? Apakah keputusanku memblokir Bram adalah hal yang tepat? Dan yang paling menyakitkan: apakah aku sanggup menjalani sisa hidupku tanpa memiliki anak kandung?
Setiap malam, sebelum terlelap, aku tak kenal lelah berdoa. Meminta petunjuk, memohon kekuatan untuk tetap teguh dalam komitmen pernikahan ini. Atau mungkin, jika Tuhan mengizinkan, sebuah keajaiban yang bisa membuat rumah tangga kami lengkap dengan kehadiran seorang anak.
Suara bel pintu memecah keheningan siang itu. Aku yang sedang membereskan dapur setelah makan siang, berjalan dengan malas ke arah pintu. Mungkin tetangga, atau mungkin sales yang sering berkeliling kompleks perumahan. Aku hanya memakai daster rumahan segera memakai jilbab. Kemudian berjalan menuju pintu rumah,
Tapi jantungku seakan berhenti berdetak saat membuka pintu. Di hadapanku berdiri sosok yang selama sebulan ini kucoba lupakan - Bram. Dia masih sama seperti yang kuingat, dengan rambut hitam berantakan dan mata cokelat yang selalu bisa menghipnotisku.
"Hai," sapanya lembut, seolah tidak ada yang salah dengan kedatangannya yang tiba-tiba ini.
"Kamu... apa yang kamu lakukan di sini?" suaraku bergetar. Mataku langsung melirik ke kanan kiri, memastikan tidak ada tetangga yang melihat.
"Aku harus bertemu denganmu. Kamu memblokir nomorku, menghindar dari semua usahaku menghubungimu. Aku tidak punya pilihan lain," jawabnya dengan nada yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini.
"Tidak punya pilihan lain? Kamu gila ya? Ini rumahku dengan suamiku, Bram! Dan kamu datang di siang hari begini?"
Bersambung.
mau baca lanjutannya di karyakarsa https://karyakarsa.com/elevensanger/series/zahira-dan-hasratnya
murah agan2
ns 15.158.61.13da2