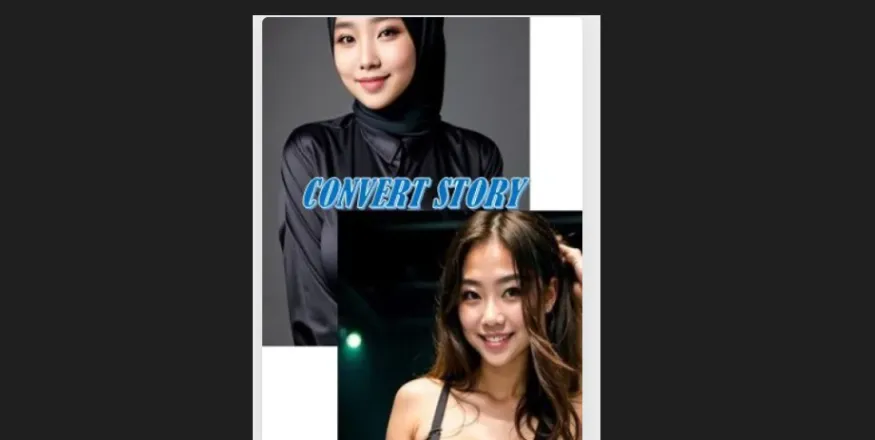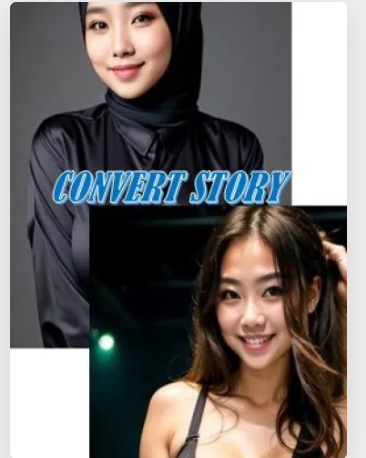 x
x
Tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, Shafira bangkit dari tempat duduknya, bergegas menuju kamarnya. Tangannya gemetar saat meraih tas, mengambil beberapa pakaian dan barang-barang penting. Dia tahu, ini adalah langkah yang sangat berisiko, tetapi di dalam dirinya, dia merasa harus melakukannya. Dia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang harapan orang lain, bahkan jika itu adalah orang tuanya sendiri.
Dengan langkah cepat, Shafira keluar dari kamarnya, mengendap-endap menuju pintu belakang. Di sana, Jefry sudah menunggunya. Pria itu berdiri dengan tenang, ekspresinya serius. Meskipun tidak banyak bicara, Shafira tahu bahwa Jefry mengerti sepenuhnya apa yang sedang dia alami.
"Kamu yakin?" tanya Jefry, suaranya datar tapi penuh dengan keprihatinan. "Ini keputusan besar, Shafira. Sekali kamu pergi, nggak ada jalan balik."
Shafira mengangguk, menatap Jefry dengan mata yang mantap meski hatinya bergejolak. "Aku nggak punya pilihan lain. Aku nggak bisa hidup seperti ini, Jef. Aku harus keluar dari sini."
Jefry tidak banyak bertanya lagi. Dia meraih tas Shafira dan memandang ke arahnya, memberi isyarat untuk mengikuti. “Ayo.”
Dengan langkah yang lebih cepat, mereka berjalan menuju gerbang belakang rumah. Angin malam yang dingin menyapu wajah Shafira, membawa perasaan aneh—antara kebebasan dan ketakutan. Mereka tidak mengatakan sepatah kata pun selama perjalanan keluar dari rumah. Diam-diam, Shafira menoleh ke belakang, melihat rumah besar tempat ia tumbuh. Di sana, di dalamnya, ada orang tua yang selalu mencintainya, yang sekarang pasti sedang patah hati.
"Aku nggak percaya aku melakukan ini," bisik Shafira saat mereka sudah jauh dari rumah. "Aku nggak pernah berpikir akan kabur seperti ini."
Jefry menoleh ke arahnya, matanya masih tetap tenang. "Kadang, kita harus mengambil keputusan sulit, Shafira. Kamu tahu itu."
Shafira menatap langit malam yang gelap, merasa kosong tapi juga ringan. Di sisi Jefry, dia merasakan sesuatu yang aneh—rasa aman, meskipun mereka sedang dalam situasi yang paling tidak pasti.
Dengan membawa beberapa barang penting, Shafira pergi meninggalkan rumah yang selama ini melindunginya, memilih jalan yang penuh dengan ketidakpastian bersama pria yang dia cintai. Bagi Shafira, ini adalah satu-satunya cara untuk mengejar kebahagiaan yang dia inginkan, meski harus melawan norma dan harapan keluarga serta masyarakat. Shafira berjalan cepat di samping Jefry, membawa tas kecil berisi barang-barang penting yang sempat ia kumpulkan. Malam semakin larut, dan suasana sekitar terasa begitu sunyi. Jalan-jalan yang biasanya ia lalui dengan penuh kenyamanan kini menjadi saksi bisu atas keputusannya yang tak terduga. Mereka bergerak melewati gang-gang sempit di pinggiran kompleks perumahan mewah, menghindari jalan utama agar tidak menarik perhatian siapa pun.
Sesekali, Jefry menoleh ke arah Shafira, memastikan bahwa dia baik-baik saja. Meskipun keputusan ini penuh risiko, Shafira tidak menunjukkan keraguan. Dia tahu bahwa melawan norma dan harapan keluarganya adalah jalan yang berat, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengejar kebebasan dan kebahagiaan yang ia dambakan.
"Apa kamu baik-baik saja?" Jefry bertanya saat mereka tiba di perempatan jalan yang sepi. Lampu jalan yang redup membuat bayangan mereka memanjang di trotoar yang dingin.
Shafira mengangguk, meskipun dadanya berdebar hebat. "Aku baik-baik saja. Teruskan saja."
Langkah mereka berlanjut melewati daerah kota yang mulai tertidur. Shafira merasakan denyut kehidupan yang berbeda dari apa yang biasa ia alami. Jalan-jalan kecil yang dipenuhi warung-warung yang sudah tutup, bangunan tua dengan cat yang mulai pudar, semuanya jauh dari kenyamanan rumah mewah yang selama ini melindunginya. Namun, entah bagaimana, ada kehangatan tersendiri yang ia rasakan. Mungkin karena di tempat-tempat seperti inilah, kehidupan terasa lebih nyata.
Mereka melewati stasiun kereta yang gelap dan lengang, di mana beberapa orang terlihat duduk di bangku, menunggu kereta pertama esok pagi. Shafira memandang mereka sejenak—orang-orang yang hidup dengan cara yang berbeda dari dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah mereka juga merasa terbebani oleh harapan dan norma yang mengekang, seperti dirinya?
“Apa kita akan naik kereta?” tanya Shafira pelan, suaranya bergetar karena lelah.
Jefry menggeleng. "Belum saatnya. Kita ke tempat yang lebih aman dulu."
Mereka terus berjalan melewati jembatan yang membentang di atas sungai kecil. Air di bawahnya mengalir dengan suara gemericik yang menenangkan, kontras dengan ketegangan yang Shafira rasakan dalam dadanya. Di kejauhan, lampu-lampu kota terlihat seperti titik-titik cahaya yang bergerak lambat, sementara di sekitar mereka hanya ada suara langkah kaki dan angin malam yang berembus lembut.
Setelah beberapa jam, mereka sampai di sebuah perkampungan kecil yang tersembunyi di balik jalan raya besar. Di sini, suasananya jauh lebih tenang, jauh dari hiruk pikuk kota. Rumah-rumah sederhana berdiri di sisi jalan, dengan cahaya lampu kuning yang temaram di dalamnya. Jefry membawa Shafira ke sebuah rumah kos-kosan yang tampak sepi, hanya diterangi satu lampu di terasnya.
"Inilah tempatnya," kata Jefry dengan nada pelan. "Untuk sementara kita bisa berlindung di sini."
Shafira dan Jefry berdiri di depan rumah kos-kosan itu, memperhatikan setiap sudutnya dengan seksama. Bangunannya sederhana, berdinding cat krem yang sudah mulai memudar, dengan beberapa tanaman dalam pot yang menghiasi teras. Tidak besar, tidak mewah, tetapi ada sesuatu yang membuat hati Shafira terasa damai. Mungkin karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas—bebas dari segala tuntutan dan ekspektasi yang selama ini membelenggunya.
Jefry mengangguk pelan, seolah merasakan hal yang sama. “Nggak jelek-jelek amat ya, Fir. Cocok buat kita yang nggak butuh banyak ribet.”
Shafira tersenyum tipis, matanya masih menyapu bangunan itu. "Iya, Jeff. Di sini, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang ngurusin latar belakang keluarga atau segala macam aturan. Cuma aku, kamu, dan tempat kecil ini."
Mereka melangkah masuk ke dalam, disambut oleh seorang ibu-ibu paruh baya yang ramah. Wajahnya tersenyum lebar, menampakkan beberapa kerutan halus yang menandakan pengalaman hidupnya.
“Selamat pagi, Nak. Cari kos-kosan ya?” tanyanya dengan nada yang penuh kehangatan.
“Iya, Bu,” jawab Jefry dengan sopan. “Kami butuh kamar untuk berdua, yang nyaman dan tenang.”
Ibu kos itu mengangguk. “Ada, Nak. Kebetulan masih ada kamar kosong di lantai dua. Gimana kalau kalian lihat dulu?”
Shafira mengangguk pelan, lalu mengikuti ibu kos itu menaiki tangga kayu yang sedikit berderit saat diinjak. Setiap langkah terasa seperti sebuah petualangan baru, meninggalkan jejak masa lalu yang ingin dia kubur dalam-dalam.
Begitu tiba di lantai dua, ibu kos membuka sebuah pintu kayu dengan kunci yang sedikit berkarat. Di balik pintu itu, terlihat sebuah kamar sederhana dengan dinding berwarna putih, jendela yang menghadap ke halaman belakang, dan sebuah ranjang kecil di sudut ruangan.
“Ini kamarnya, Nak. Memang nggak terlalu besar, tapi tenang. Biasanya anak-anak kos di sini juga nggak terlalu berisik,” jelas ibu kos sambil tersenyum.
Shafira melangkah masuk, merasakan kehangatan dari cahaya matahari yang masuk melalui jendela. Dia memandang sekeliling, merasakan ketenangan yang aneh namun menyenangkan. “Ini cukup buat kita, Jeff. Nggak perlu yang mewah-mewah,” ucapnya dengan suara lembut.
Jefry menghampiri jendela, melihat pemandangan sederhana di luar sana—beberapa pohon rindang dan suara burung yang berkicau. “Iya, Fir. Ini pas. Di sini kita bisa mulai semuanya dari awal, tanpa gangguan.”
Ibu kos mengangguk setuju. “Kalau kalian merasa cocok, langsung aja, Nak. Harga sewanya juga nggak mahal, dan kalau ada apa-apa, ibu selalu ada di bawah.”
“Terima kasih, Bu,” kata Shafira tulus. “Kami ambil kamar ini.”
Setelah berbicara soal harga sewa dan beberapa aturan kecil lainnya, mereka resmi mendapatkan kamar itu. Saat ibu kos meninggalkan mereka untuk membereskan administrasi, Shafira duduk di ranjang, merasakan perasaan lega yang perlahan mengalir dalam dirinya. Dia menatap Jefry, yang kini duduk di sebelahnya, dan berkata pelan, “Jeff, ini langkah pertama kita, ya? Semoga nggak ada yang nyesel.”
Jefry menggenggam tangan Shafira erat. “Nggak akan ada yang nyesel, Fir. Kita di sini buat ngejar kebahagiaan kita sendiri. Nggak peduli apa kata orang lain.”
Shafira tersenyum, merasakan keyakinan dalam kata-kata Jefry. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa benar-benar bebas. Bebas untuk memilih, bebas untuk mencintai, dan bebas untuk mencari kebahagiaannya sendiri, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menghantui.
Mereka masuk ke dalam kamar kos, dan Shafira merasa lega. Ruangannya sederhana, dengan perabotan yang minimalis. Jefry menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, cahayanya memantul lembut di dinding kayu.
"Besok pagi, kita bisa pikirkan langkah selanjutnya," ujar Jefry, duduk di lantai dan menatap Shafira yang duduk di depannya. "Sekarang, kamu istirahat dulu. Kamu butuh tidur."
Shafira mengangguk, meskipun pikirannya masih terus berputar. Keputusan yang diambilnya tadi malam akan mengubah segalanya—hidupnya, hubungannya dengan keluarga, bahkan masa depannya. Tapi di sisi lain, ada rasa lega yang mulai tumbuh di hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa bebas untuk membuat pilihan yang benar-benar miliknya.
Malam itu, Shafira tertidur dengan perasaan campur aduk. Di luar, angin malam masih berembus, membawa ketenangan yang pelan-pelan menyelimuti hatinya. Jalan yang penuh ketidakpastian ini baru saja dimulai, tetapi untuk pertama kalinya, dia merasa siap menghadapi apa pun yang akan terjadi.
****
Di kos-kosan kecil yang mereka sewa, Shafira merasakan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya—kebebasan. Kamar sempit dengan dinding bercat putih kusam dan perabotan sederhana ini jauh dari kemewahan yang selama ini mengelilinginya, namun di tempat inilah, Shafira merasa lebih hidup daripada di rumah besar keluarganya.
Dia duduk di lantai sambil menyeruput kopi dari gelas plastik. Di luar, suara-suara kehidupan sederhana terdengar jelas: tawa anak-anak bermain, deru motor berlalu-lalang, dan suara para penghuni kos lainnya yang bercengkerama di teras. Shafira memandang Jefry, yang sedang sibuk memperbaiki kipas angin di sudut ruangan. Kehidupan mereka mungkin sederhana sekarang, tapi baginya, kebersamaan ini lebih berharga daripada segala hal yang pernah ia miliki sebelumnya.
"Jef, aku nggak nyangka bisa sesenang ini," kata Shafira sambil tersenyum lebar.
Jefry menoleh, senyum tipis terukir di wajahnya. "Ya, begini rasanya hidup tanpa beban. Meskipun sederhana, tapi semua pilihan ada di tangan kita sendiri."
Shafira mengangguk, merasakan betul kata-kata Jefry. Dulu, setiap keputusan hidupnya selalu dikendalikan oleh harapan orang tua dan tuntutan masyarakat. Menjadi anak dari Ustadz Farid Othman, dikenal semua orang, membuat kebebasan terasa jauh di luar jangkauan. Tapi sekarang, dia bisa menjalani hidup yang dipilihnya sendiri—bersama Jefry, jauh dari sorotan dan tuntutan.
Setiap hari mereka jalani dengan kesederhanaan. Bangun pagi untuk bekerja, memasak bersama, dan berbagi tawa di malam hari. Shafira merasa seperti menemukan kembali jati dirinya yang hilang selama ini. Tidak ada lagi pakaian mahal, tidak ada acara-acara bergengsi, hanya Shafira dan Jefry, menjalani hari-hari dengan kehangatan dan kejujuran.
"Kos-kosan ini memang kecil, tapi rasanya lebih besar daripada rumah yang dulu," kata Shafira suatu malam, saat mereka berbaring di lantai, menatap langit-langit kamar yang rendah.
Jefry tertawa pelan. "Kamu memang aneh, Shafira."
"Tapi kamu mengerti kan? Aku merasa lebih bebas sekarang. Aku bisa menjadi diriku sendiri."
"Ya, aku mengerti," jawab Jefry. "Dan selama kamu bahagia, aku juga bahagia."
Shafira tersenyum, merasa hati mereka semakin dekat. Dalam kesederhanaan ini, dia menemukan kebahagiaan sejati—sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam kemewahan hidupnya yang dulu.
Malam itu, di bawah cahaya redup lampu kos-kosan yang sederhana, Shafira merasakan sesuatu yang baru. Setelah melalui semua gejolak dan pelarian, ketenangan mulai merasuk ke dalam hatinya. Bersama Jefry, dia menemukan kedamaian dan keintiman yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya.
Jefry menatapnya dalam diam, ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Shafira merasa aman dan terlindungi. Di dalam kamar yang kecil dan sederhana, hanya ada mereka berdua, terhubung dalam keheningan yang penuh arti.
Shafira merasa jantungnya berdebar lebih cepat saat Jefry mendekat, jemarinya menyentuh lembut pipinya. "Kamu pasti capek, ya?" suara Jefry terdengar pelan, hampir seperti bisikan.
Shafira menggelengkan kepala, tapi senyumnya tetap terlihat. "Aku nggak pernah selega ini," katanya dengan suara yang hampir bergetar. "Aku merasa hidup... sungguh hidup."
Malam itu, kehangatan yang muncul di antara mereka berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Tangan Jefry bergerak lembut menyentuh rambut Shafira, dan dalam pelukan yang erat, mereka mulai tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Cinta yang terpendam, yang selama ini terhalang oleh norma dan batasan, akhirnya menemukan jalannya untuk bebas.
Setiap sentuhan terasa begitu intim, begitu penuh makna. Mereka bercinta bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan perasaan yang begitu mendalam. Shafira merasa setiap detik bersama Jefry adalah sebuah keajaiban—bahwa dia akhirnya menemukan tempat di mana dia bisa sepenuhnya menjadi dirinya, tanpa topeng, tanpa tekanan.
Dalam kegelapan malam yang sunyi, mereka hanyut dalam asmara, seakan dunia di luar sana tak lagi penting. Bagi Shafira, ini adalah momen di mana cinta dan kebebasan bertemu, menghapus segala keraguan dan rasa bersalah yang pernah menghantuinya.
Saat mereka akhirnya berbaring bersama, tubuh mereka saling merapat dalam kehangatan yang sempurna, Shafira menatap Jefry dengan mata yang berbinar. "Aku bahagia," bisiknya, suara yang terdengar seperti sebuah pengakuan, bukan hanya untuk Jefry, tapi juga untuk dirinya sendiri.
Jefry tersenyum, menariknya lebih dekat. "Aku juga, Shafira... aku juga."
Malam itu, mereka berdua bukan hanya tenggelam dalam asmara, tapi juga dalam cinta yang tulus—cinta yang lahir dari kebebasan dan ketulusan, yang selama ini mereka cari.
Hari itu datang lebih cepat daripada yang Shafira bayangkan. Mereka baru saja pulang dari pasar, membawa sayuran dan beberapa kebutuhan sehari-hari, ketika tiba-tiba suara deru mobil polisi memenuhi gang sempit tempat mereka tinggal. Shafira menoleh dengan bingung, melihat dua mobil patroli berhenti tepat di depan kos-kosan mereka.
Jefry, yang berada di sampingnya, langsung tegang. Mata mereka bertemu, dan di dalam tatapan Jefry, Shafira bisa melihat rasa takut yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebelum mereka sempat mengatakan apa pun, beberapa polisi turun dari mobil dan langsung menghampiri mereka.
"Jefry Fernandes?" salah satu petugas bertanya dengan nada tegas.
Jefry tidak menjawab, dia hanya memandang Shafira dengan cemas.
"Saya," jawabnya pelan, suara Jefry bergetar, sesuatu yang jarang terjadi. Shafira merasakan dunia di sekitarnya mulai kabur, seolah-olah waktu berhenti. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak sekarang, tidak setelah semua yang mereka lalui.
"Kami harus membawa Anda ke kantor polisi. Anda dilaporkan oleh keluarga Farid Othman atas tuduhan membawa lari anak gadis mereka."
"Tidak!" Shafira melangkah maju, suaranya memecah ketegangan. "Dia tidak membawa aku lari! Aku yang pergi dengan keinginanku sendiri! Jangan bawa dia!"
Para petugas tidak mendengarkan. Dua dari mereka dengan cepat mengeluarkan borgol dan mengunci pergelangan tangan Jefry. Shafira berusaha meraih tangan Jefry, namun tubuhnya dicegah oleh salah satu petugas.
"Jangan! Tolong, jangan bawa dia!" Shafira menjerit, airmatanya mengalir deras. "Kami saling mencintai. Ini bukan salah dia!"
Jefry menatap Shafira dengan tenang, meskipun ketakutan jelas terpancar di wajahnya. "Shafira, tenang... Jangan khawatir. Ini bukan akhir."
"Tapi aku nggak bisa kehilangan kamu!" Shafira berusaha melepaskan diri, tubuhnya gemetar saat melihat Jefry yang mulai dibawa masuk ke mobil polisi. "Kamu janji... kita akan bersama selamanya. Kamu nggak boleh pergi!"
Namun, Jefry sudah dibawa menjauh, tangannya diborgol, sementara wajahnya masih mencoba memberikan ketenangan untuk Shafira. "Aku akan baik-baik saja. Aku janji, Shafira."
Shafira hanya bisa menatap dengan perasaan hancur ketika mobil polisi itu berlalu, membawa pergi satu-satunya orang yang ia cintai. Dunia yang baru saja ia bangun bersama Jefry hancur dalam sekejap, dan perasaan kebebasan yang sempat ia rasakan menguap, tergantikan oleh kepedihan dan rasa kehilangan yang begitu dalam.
Saat malam tiba, Shafira hanya bisa duduk di kamar mereka yang kini terasa kosong, memandangi dinding dengan mata kosong. Tanpa Jefry, segalanya terasa hampa. Kebahagiaan yang pernah ia rasakan kini seolah menjadi mimpi yang jauh dari jangkauannya.
Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, meski lampu kos-kosan tetap menyala redup. Shafira duduk memeluk lutut di sudut kamar yang kini hanya dihuni oleh dirinya seorang. Tidak ada Jefry, tidak ada suara canda yang dulu mengisi keheningan. Dunia Shafira hancur, dan dia tidak bisa menahan amarah yang semakin hari semakin membara dalam dadanya.
Dia memandangi ponsel di tangannya, deretan pesan dan panggilan tak terjawab dari ibunya, Senaiya. Semua pesan itu serupa—memohon agar Shafira pulang, menekankan bahwa semua ini untuk kebaikannya. "Kebaikan?" Shafira mendengus kesal. Kebaikan macam apa yang memenjarakan orang yang dia cintai? Keluarganya yang selalu berusaha terlihat sempurna di mata masyarakat, sekarang terlihat kejam dan egois di mata Shafira.
Saat itu, ponselnya kembali berdering. Nama ibunya muncul di layar. Dengan perasaan yang sudah terlalu penuh, Shafira akhirnya mengangkatnya.
“Shafira, nak, kapan kamu mau pulang?” suara lembut ibunya terdengar dari seberang telepon, penuh dengan kecemasan dan kerinduan.
Shafira terdiam sesaat, berusaha mengendalikan emosinya. Namun kemarahannya sudah terlalu besar untuk dibendung. “Aku nggak akan pulang, Bu,” jawabnya dingin.
“Shafira, sayang, kamu nggak bisa terus begini. Kami melakukan ini demi kamu, nak. Hilmy adalah pilihan terbaik untukmu, daripada Jefry, umi gak ngerti kenapa kamu bisa sama Jefry yang…"
“Jefry yang apa, umi?” potong Shafira, nadanya mulai meninggi. “Kalian mau bilang dia nggak pantas buat aku, tapi justru dia yang membuat aku merasa hidup! Apa kalian pikir bisa mengatur semuanya dalam hidupku? Bahkan menentukan siapa yang harus aku nikahi?”
Senaiya terdiam di ujung telepon. “Nak, kami hanya ingin yang terbaik. Kamu tahu bagaimana dunia ini...”
Shafira tertawa sinis. “Yang terbaik menurut kalian, umi. Selama ini kalian nggak pernah dengar apa yang aku inginkan! Aku muak dengan semua aturan ini, semua harapan ini. Aku nggak ingin hidup seperti ini lagi.”
“Shafira...” Senaiya suaranya mulai terdengar gemetar. “Jangan bicara seperti itu, nak. Kamu adalah anak yang beriman, anak yang tahu mana yang benar dan salah.”
Mendengar kata-kata itu, kemarahan Shafira meledak. “Iman? Kalian bicara tentang iman saat kalian memenjarakan orang yang aku cintai? Aku nggak peduli lagi! Aku nggak butuh iman kalian. Aku nggak mau jadi bagian dari dunia kalian lagi!”
Senaiya terkejut, nadanya berubah penuh ketakutan. “Shafira... jangan bilang begitu. Kamu tahu apa artinya itu. Jangan sembarangan bicara, nak. Apa yang kamu bicarakan?”
Shafira menghela napas panjang, air mata menggenang di matanya, tapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. “Aku nggak mau jadi bagian dari keluarga ini lagi. Aku juga nggak mau jadi bagian dari apa yang kalian percayai. Mulai sekarang, aku akan menjalani hidupku sendiri. Tanpa kalian. Dan tanpa iman yang selalu kalian paksa padaku.”
Di seberang sana, Senaiya menangis, tapi Shafira tidak lagi mendengarkannya. Dengan satu gerakan tegas, dia menutup telepon itu dan melemparkannya ke tempat tidur. Dunianya mungkin sudah hancur, tapi kali ini dia bertekad untuk membangunnya kembali sesuai dengan keinginannya sendiri, meskipun itu berarti meninggalkan segalanya—termasuk keyakinannya.
Diam-diam, Shafira mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia memilih untuk meninggalkan agama yang selama ini dianutnya. Baginya, Tuhan telah meninggalkan dirinya ketika keluarganya memisahkannya dari Jefry. Ia merasakan kepahitan yang dalam, dan kebenciannya hanya semakin membara.
Beberapa bulan kemudian, Shafira membuat langkah yang mengejutkan. Ia memutuskan untuk menjadi seorang selebgram. Dengan penuh tekad, ia menghapus foto-foto lamanya yang masih mengenakan hijab. Ia merasa hijab itu adalah simbol pengekangan yang dipaksakan keluarganya. Kini, ia ingin bebas, sepenuhnya.
Hari pertama ia muncul di Instagram tanpa hijab, dunia maya heboh. Komentar netizen membludak di setiap postingannya. Ada yang mendukung, ada yang mengecam, tapi Shafira tak peduli. Dia merasa hidupnya kini miliknya sendiri.
Bersambung
ns 15.158.61.12da2