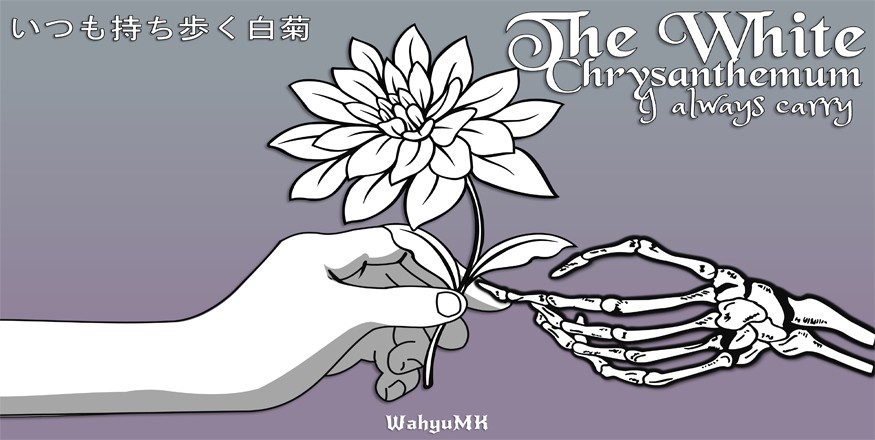Setelah makan, aku mencuci semua piring dan peralatan memasak. Sedangkan Ventine-san masih duduk di ruang makan sambil menikmati ginger ale. Kami mengobrol santai.
Aku bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya terjadi.
“Umm… yang aku ingat cuma….” Ia menjentikkan jarinya satu per satu. “Pertama… aku bangun dan lapar…. Kedua… aku nggak punya apa – apa selain baju…. Ketiga… aku harus cari makan. Keempat… aku nggak bisa hidup dengan orang yang kekurangan…. Kelima… aku ingin seseorang memungutku,” balasnya dengan santai dan tempo agak lambat.
(Huh? Santai sekali nona berwajah datar ini bilang mungut?)
“Heehhh~ Karena itu kamu menolak Hisae-san?”
“Umm… Hisae?”
“O-oh, ah. Nggak masalah, lupakan,”
(Aku lupa kalau Ventine-san nggak seberapa mengenal dengan tunawisma sekitar.)
“Oh… wanita… yang tidur di… tenda?”
“Y-ya….” Aku mengangguk.
Ventine-san, dari ekpresi dan intonasi suaranya sangat datar mirip robot. Bahkan ia seperti gadis kecil linglung dan cara berpikirnya agak lambat.
(Maksudku, bagaimana bisa wanita linglung sepertinya berakhir seperti tadi? Bukannya Drone pengawas pemerintahan juga masuk ke gang kecil?)
“Maaf, tapi di mana rumah Ventine-san?”
“Umm… rumah…?” tambahnya sambil memutar – mutar kaleng ginger ale saat kuperhatikan dari belakang. “Seperti tempat ini…?”
“Y-ya… semacam itu. Rumah adalah tempat kamu bisa melakukan apa saja. Tiduran, main game, memasak, bersih – bersih, atau nonton TV…”
“W-woah! Ven-ventine… bisa melakukan semua itu?” Matanya berbintang cerah dan perangainya menjadi bersemangat.
(Hey, hey, kok malah balik tanya?)
Aku menepuk jidatku sendiri. Agak susah mengupas cangkangnya. Terutama cangkang yang paling keras adalah orang lamban dan lingung seperti Ventine-san.
Kupikir, aku harus mengganti pertanyaanku.
“Begini… apa yang Ventine-san ingat setelah bangun? Ma-maksudku… seperti di sebuah kamar? Atau…?”
“Umm….” Ventine-san diam sejenak. Kerutan di dahinya dan bibirnya yang mencucu tampak seperti Ventine-san dalam keadaan berkonsentasi.
Sementara itu…
Semua cucian piring sudah bersih, kini aku duduk di hadapaannya sambil meneguk Ginger ale yang sedari tadi belum kusentuh sama sekali.
“Waaaa~!” Wanita berambut hitam panjang lurus dengan paras datar, Ventine-san, mengangkat jarinya, sambil bibirnya membuka. Matanya dipenuhi kilatan emas, seolah menemukan bakal jawaban di dahan otaknya.
(Apakah pertanyaanku sesusah itu?)
“Anu….” Ia menatap tepat lurus dan telunjuknya menunjuk padaku.
“ah, Chiba Takeichi,”
“Chiba…~ Ventine ingat sekarang…!” kini wajahnya tampak serius. “Kelap – kelip!”
Entah bagaimana, melihat wajahnya serius aku mulai penasaran.
“Kelap – kelip?” kataku sambil memperhatikan setiap katanya yang terlihat seperti petunjuk penting.
“Uh-huh… uh-huh….” Ventine-san mengangguk – angguk kecil. “Segi enam….”
“Se-segi enam?”
“Ya… ya….” tambahnya. “Kasur hijau…,”
“Ka-kasur hijau?”
(Apa ini semacam tebak – tebakan? Heh! Kuharap itu nggak dibuat mudah. Pfft! Nggak ada tebakan yang nggak bisa kupecahkan!)
Ventine-san mengangguk kesekian kalinya.
“Ular panjaaaannggg! Dan… suara radio…,” tambahnya. “Itu yang Ventine ingat,”
Kedua kalinya aku menepuk jidat.
(Oke, aku menyerah. Memahaminya saja sudah sulit, apalagi latar belakangnya. Hah….)
“Ada apa? Chiba, sakit…?” Ventine-san lekas menaruh tangannya memegang dahiku. Roman mukanya menjadi khawatir. Bahkan nadanya yang memanjang itu, terdengar sangat halus dan nyaman didengar.
“Ah nggak-“ Aku merasakan tangan Ventine-san terasa agak panas. “Eh?
(Apa dia demam? Nggak kaget sih kalau kena hujan deras dan angin kencang kayak tadi.)
Aku segera menaruh telapak tangan kananku pada dahinya. Karena kurang yakin, sebagai gantinya aku mendekatkan dahiku sendiri padanya untuk lebih pasti.
Kini, aku bisa melihat Ventine-san dengan sagat dekat. Bahkan, aku merasakan nafasnya yang agak tersengal – sengal. Agak mengejutkan dari yang terlihat dan disangkanya orang gila, kenyatannya menyimpan pesona wajah bak putri tidur.
“Uhh…” Ventine-san memekik kecil.
Ngomong – ngomong…
Poin pentingnya adalah, dahinya terasa lebih panas dari dahiku. Nafasnya juga tersengal – sengal dan bola matanya yang lumayan merah disertai warna hitam di seklilingnya.
“Chiba….”
“Apa?”
“Anu… jangan menatapku begitu…. Aku… agak malu….” Pipinya sedikit memerah. Ventine-san segera mengalihkan bola matanya pandangnya.
Aku spontan menjauhkan diri. “Maaf! Aku hanya memeriksa suhumu dengan perkiraan. Kamu agak demam Ventine-san,”
Aku segera beranjak dan mengambil kotak obat di atas kulkas. Kemudian kembali duduk.
“Umm… demam?”
“Nggak usah khawatir, siapapun yang kena hujan deras dan angin kencang kayak tadi pasti demam. Katakan, kamu pusing?” Aku membuka kotak obat itu dan mencari – cari nama obat. “Paracetamol… paracetamol….”
Ventine-san mengangguk pelan.
“Uh-huh. Rasanya… ingin tidur… sebentar,”
Mata Ventine-san kini sayu – sayu. Bahkan kepalanya agak kehilangan keseimbangan.
“Oke, setelah minum langsung tidur ya.” Aku menyodorkan satu kaplet obat penurun demam yang kubeli seminggu yang lalu. Masih belum tersentuh. Tapi, aku kembali khawatir pada nona berwajah datar ini.
(Ja-jangan bilang dia nggak tahu caranya minum obat?)
Karena khawatir, aku memperhatikan Ventine-san terlebih dahulu.
Ventine-san menuang air dispenser pada gelas. Lantas, disobeknya bungkus aluminium foil pada kanan teratas. Sebuah tablet kini terpegang jarinya. Saat hendak membuka mulutnya, Ventine-san…
“Chiba…, kamu sakit?” Ventine-san yang keheranan tiba – tiba berpaling ke arahku.
“Uhh-ehh? E-enggak!” Kali ketiganya aku menepuk jidat. “Silahkan diminum,”
(Benar juga! Ngapain aku khawatir? Orang bodoh macam mana yang nggak bisa menelan obat?)
Ventine-san meminum obat seperti orang pada umumnya. Ia akhirnya menelan tablet penurun demam itu. Lantas, aku mengarahkannya ke kamar Yuka.
Kamar yang… sudah lama nggak ditiduri siapapun. Kamar itu sangat sederhana, dengan tembok putih seperti kamarku dan hampir nggak ada bedanya. Cuma satu hal.
Lemari Yuka. Lemari besar berbahan kayu besi dengan ukiran rumit. Bentuknya nggak cuma persegi panjang yang ditaruh vertikal dan membosankan, melainkan dibuat seperti setengah lingkaran di bagian atasnya. Kedua pintunya terukir wanita dengan pakaian bangsawan dari entah india atau mesir, yang jelas di era kuno.
“Ohhh….” Ventine-san tampaknya terkejut dengan lemari besar Yuka.
“Kamu suka, Ventine-san?”
“Ventine… nggak pernah lihat yang seperti ini….”
Aku mengatakan padanya bahwa itu dulunya kubeli pada kakek yang sangat butuh uang demi membayar operasi ginjal di rumah sakit. Namun, Yuka menegurku untuk nggak membeli murah. Aku juga sadar diri walau nggak diberitahu, lagipula ukiran ini meski aku nggak mengerti seni. Pasti harganya lebih dari 60 ribu yen. Jadi, aku membelinya dengan harga tiga kali lipatnya, tunai.
“Yuka… orang baik. Chiba… juga.”
“Hm… terima kasih?” Aku menggaruk kepalaku. Aku nggak tahu harus merespon bagaimana, tapi Ventine-san membuatku sedikit tersipu.
Setelah itu, Ventine-san merebahkan diri di kasur. Aku lega saat kepalanya merasa nyaman bersandar di bantal latex itu daipada trotoar.
Setelah mengucapkan selamat malam padanya, aku juga lekas membenamkan diri pada kasurku.
Ponsel menunjukkan pukul 23.45…
Aku nggak percaya selarut ini. Aku harus jaga kondisi. Lagipula pekerjaanku, keduanya mempunyai jam terbang dan tanggung jawab yang ketat. Seenggaknya mereka membayarku mahal, aku nggak terlalu protes.
Hanya saja…
Aku berharap ada pekerjaan lain. Faktanya, setelah 3 tahun Dai-san mengundurkan diri….
Selama 3 tahun pula…
Mental dan fisikku dibenturkan tanpa henti. Aku sudah diambang batas.
Aku benci jam kerja yang tolol!
Maksudku… apakah seorang software engineer lumrah bekerja mulai pukul 04.30 pagi?
***
ns 15.158.61.8da2